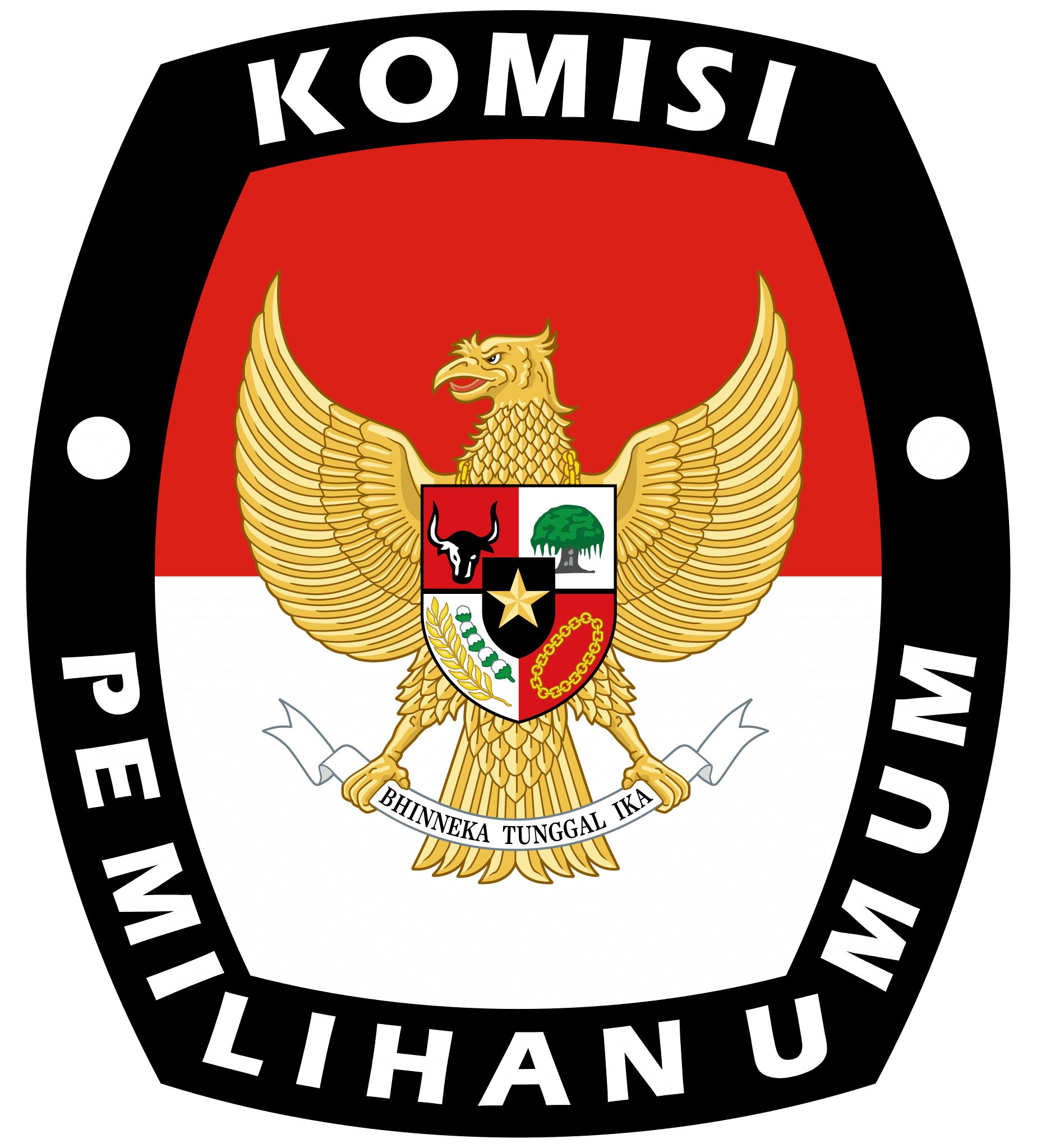Tantangan Implementasi E-voting Pemilu di Indonesia
Adopsi e-voting dalam Pemilu dan Pilkada merupakan tantangan reformasi birokrasi di Indonesia. E-voting adalah perhitungan suara dalam pemilu dengan menggunakan komputer atau peralatan yang terkomputerisasi (Cetinkaya et al, 2007). Dari definisi tersebut, e-voting merujuk pada adopsi teknologi untuk membantu perhitungan suara dalam pemilu dan pilkada.
E-voting di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2010 di Kabupaten Jembrana, penerapannya ada di pilkades Desa Mendoyo Dangin Tukad. Pemilihan kepala desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad diatur dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2010 tentang pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Pelaksanaan e-voting di desa ini telah mendapatkan legalitas dari Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga hasil pilkades dengan e-voting tersebut akuntabel. (Made et al, 2014)
Sumber : INTI Group (inti.co.id), 2023.
Dalam pelaksanaannya, ada sekitar 2000 desa yang telah menggunakan sistem e-voting di Indonesia yang tersebar dari 15 provinsi dan 28 kabupaten termasuk Boyolali, Jembrani, Musi Rawas dan Indragiri Hilir. Dari trial yang dilaksanakan tersebut, e-voting mampu mengatasi masalah DPT ganda, beban anggaran serta efisiensi waktu penyelenggaraan pemilu. (INTI, 2023)
Jika kita membandingkan dengan negara demokrasi terbesar di dunia yakni India, mereka telah implementasikan e-voting sejak 1982 dengan menggunakan Electronic Voting Machines (EVMs). Setiap pemilih yang menggunakan mesin tersebut dicetak sebagai bukti dengan VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail) sebagai jejak audit untuk membangun kepercayaan serta transparansi (Aishwarya, 2025).
Beberapa faktor yang menyebabkan India pindah total dari surat suara kertas ialah biaya yang murah, yaitu hanya (200 dollar) atau sekitar (3.269.068 rupiah) per 28 Juli 2025, sederhana dan mudah digunakan, dapat bekerja dengan baterai, menyelamatkan 150.000 pohon untuk kertas suara dan kotak suara, mengurangi jumlah TPS karena dapat menampung banyak pemilih dan dapat digunakan kembali dengan pengaturan yang mudah. (Karthik G Maiya et al, 2018).
Bukan cuma India yang sukses mengimplementasikan e-voting dalam pemilu seperti Brazil, Filipina dan Estonia dengan perangkat yang berbeda seperti EVM, GX-I serta PCOS. (Risnanto et al, 2020). Perangkat tersebut bahkan bisa digunakan tanpa koneksi internet dan menggunakan internet hanya untuk perhitungannya.
Kelebihan dari e-voting ialah perhitungan secara digital bisa dilakukan dengan menyetor data dari aplikasi atau mesin e-voting ke teknologi blockchain. Blockchain adalah block sederhana yang menyimpan informasi digital yang disimpan di berbagai komputer. (Aneem et al, 2019). Sehingga, dalam perhitungannya bisa disetor ke seluruh komputer dalam jaringan peer-to-peer. Ini penting untuk mencegah manipulasi data karena jika ingin mengubah informasi di satu komputer, maka perlu untuk merubah di semua komputer. Teknologi ini membantu dalam transparansi dan kepercayaan publik karena sesuai dengan asas pemilu yang Luber Jurdil.
Implementasi E-voting ini perlu banyak pertimbangan misalnya dari kerangka hukum, sumber daya manusia serta infrastruktur teknologi. Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia (Leila et al, 2024). Tantangan regulasi ini termasuk belum adanya UU yang mengatur soal E-voting dalam pemilu sehingga belum bisa dilaksanakan. Kemudian Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai karena butuh literasi teknologi yang matang sehingga dapat menggunakan aplikasii E-voting tersebut. E-voting ini perlu akses internet dan tidak semua wilayah di Indonesia ada akses Internet, contohnya di Kabupaten Sekadau banyak desa yang belum ada jaringan internet.
Kesimpulannya e-voting dalam memberikan kemudahan serta efisiensi dalam penyelenggaraannya namun tantangan implementasi seperti transfer teknologi, kerangka hukum, serta Sumber Daya Manusia (SDM) membutuhkan koordinasi dan kerjasama dari pembuat kebijakan dan pelaksananya serta peran masyarakat sipil untuk menciptakan sistem demokrasi yang akuntabel dan transparan sehingga output hasil pemilu bisa dipercaya oleh publik.
Penulis : Rinaldo Farera
Aishwarya. 2025. Why India's electronic voting machines are simplest and most secure in world. https://www.indiatoday.in/india/story/why-india-electronic-voting-machines-evm-are-simplest-and-most-secure-in-world-2707815-2025-04-13
Aneem et al, (2019). Introduction to Blockchain. https://www.researchgate.net/publication/343601688_Introduction_to_Blockchain
Cetinkaya, O., & Cetinkaya, D. (2007). Verification and validation issues in electronic voting. The Electronic Journal of E-Government, 5(2), 117–126. Diakses dari http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.90.155&rep=rep1 &type=pdf
IBM. (2025). What are smart contracts on blockchain?. https://www.ibm.com/think/topics/smart-contracts
INTI. 2023. Sukses Rampungkan Pilkades Elektronik pada Ribuan Desa, INTI Group Jadi Satu-Satunya Pemegang Legalitas Sistem e-Voting.
https://www.inti.co.id/?p=12076#:~:text=Kepala%20Dinas%20Komunikasi%20dan%20Informatika,pada%2030%20Mei%202023%20lalu
Karthik G Maiya, Vineesha. T, Veena G, and Sujay S.N. 2018. Secured Electronic Voting System Using Biometrics. Ncesc - 2018 6(13): 1–5.
Leila et al. (2024). Indonesia, the world's third largest democracy, has voted for a new president. https://www.npr.org/2024/02/14/1231313647/indonesia-the-world-s-third-largest-democracy-has-voted-for-a-new-president
Made et al. Implementasi Kebijakan Penerapan Elektronik Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa https://media.neliti.com/media/publications/165240-ID-implementasi-kebijakan-penerapan-elektro.pdf
Risnanto, Slamet. 2013. Merubah Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dari Konvensional Ke Digital (E-Pilkada). Jurnal Online Sekolah Tinggi Teknologi Mandala 6(1): 103–7
Selengkapnya