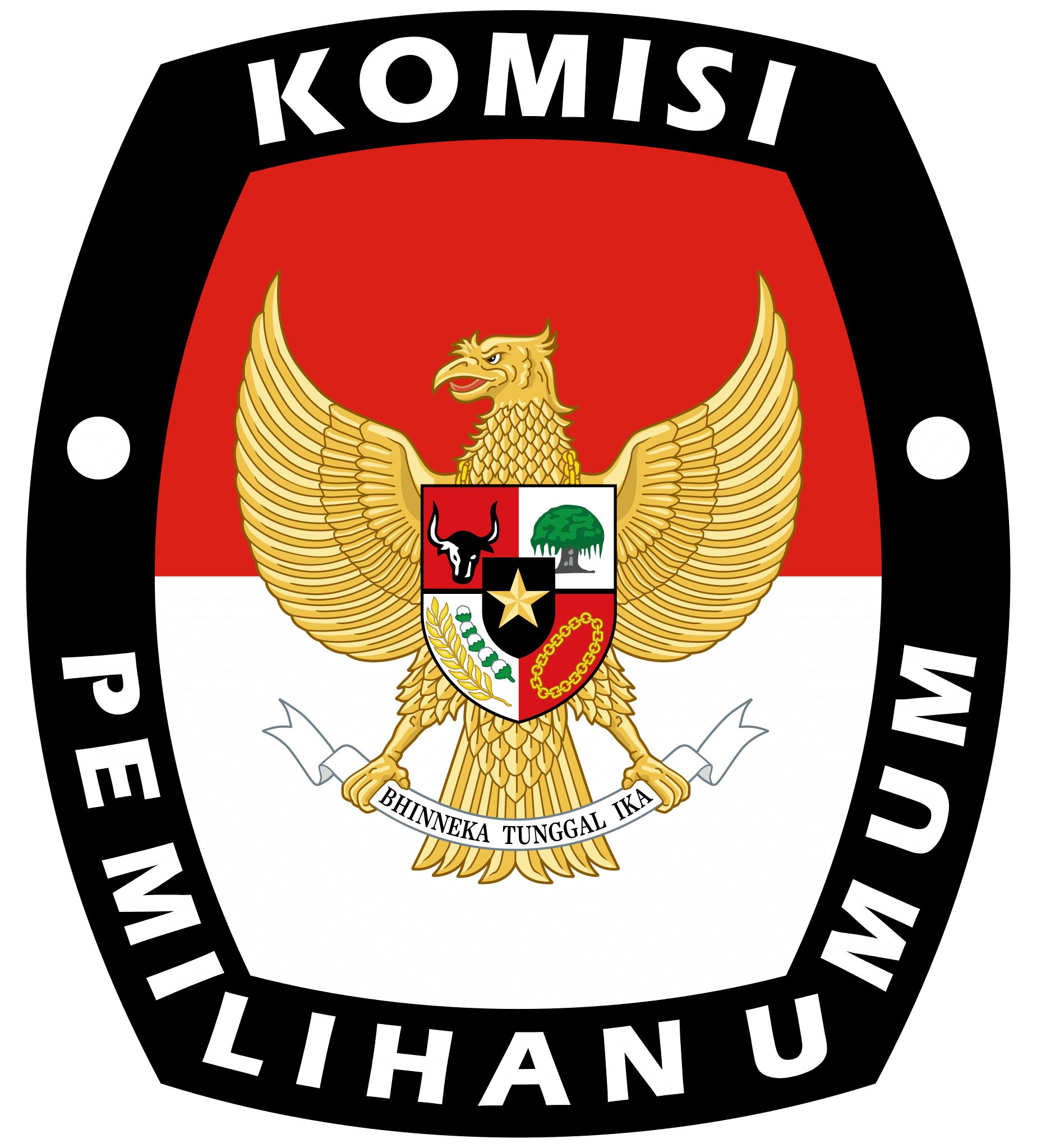PAW dan Peran KPU dalam Menjaga Demokrasi
Penulis : Radha Florida Dalam sistem demokrasi, Pergantian Antar Waktu (PAW) merupakan solusi ketika kursi wakil rakyat atau pejabat publik kosong di tengah masa jabatan. Idealnya, PAW menjaga kesinambungan pemerintahan agar roda kebijakan tetap berjalan tanpa hambatan. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini sering menimbulkan perdebatan apakah PAW benar-benar menjamin kepentingan rakyat atau justru menjadi celah kompromi politik? Di sinilah peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sangat penting. PAW biasanya terjadi karena berbagai alasan: pengunduran diri, meninggal dunia, pelanggaran hukum, hingga partai politik yang menarik anggotanya. Secara prosedural, mekanisme ini terlihat rapi: partai pengusung mengusulkan pengganti, kemudian lembaga terkait mengesahkan. Tetapi pertanyaan penting muncul: apakah suara rakyat yang dulu memilih ikut terwakili oleh pengganti ini? Hubungan antara PAW dan KPU tidak bisa dilepaskan. Setiap kali terjadi kekosongan kursi di DPRD, partai politik memang berhak mengusulkan pengganti. Namun, pengganti itu tidak bisa serta-merta ditetapkan tanpa verifikasi dari KPU. KPU tidak menentukan siapa yang diganti atau siapa penggantinya secara politis, melainkan menjalankan fungsi administratif demi menjaga integritas proses dan legitimasi parlementari. Lembaga penyelenggara pemilu ini harus meneliti kembali daftar calon tetap (DCT) hasil pemilu terakhir dan perolehan suara sah legislatif di dapil tertentu, memastikan bahwa calon yang diajukan benar-benar berasal dari perolehan suara berikutnya, bukan sekadar hasil kompromi internal partai. Kasus PAW DPRD Kabupaten Sekadau tahun 2018 menjadi cerminan nyata dari pentingnya peran KPU. Saat itu, Hendri Suhendar dari Partai Gerindra mengundurkan diri karena mencalonkan diri melalui partai lain. KPU kemudian menetapkan Harianto sebagai pengganti berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. Proses ini berjalan sesuai aturan, dan pelantikan dilakukan melalui sidang paripurna DPRD (https://senentangnews.com/read/15164/paw-dprd-sekadau-harianto-gantikan-suhendar.html). Namun, di balik kelancaran prosedural, PAW merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemilu yang demokratis, dan harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemilu: keterwakilan, kepastian hukum, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peran sentral sebagai penjaga konstitusi dan pelaksana integritas politik. Lebih jauh, KPU juga berperan dalam menjamin efisiensi dan efektivitas PAW. Dengan menjalankan prosedur secara tertib dan tepat waktu, kekosongan kursi legislatif tidak berlarut-larut, sehingga wakil rakyat tetap bisa bekerja memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, PAW sesungguhnya bukan hanya formalitas administratif, tetapi juga cermin dari bagaimana prinsip pelaksanaan pemilu diterapkan setelah hari pemungutan suara berlalu. Melalui pengawasan dan verifikasi yang profesional, KPU menjaga agar PAW tetap menjadi instrumen demokrasi yang sah, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Selengkapnya