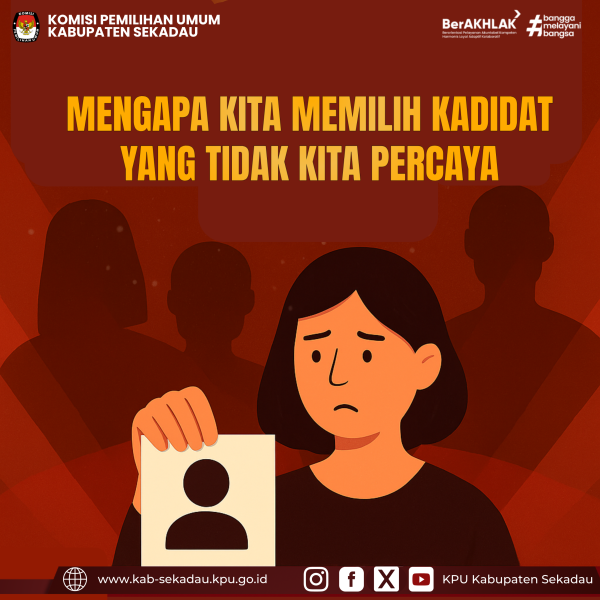
Mengapa Kita Memilih Kadidat Yang Tidak Kita Percaya
Oleh: Lidia Wenny
Fenomena masyarakat yang memilih kandidat yang sebenarnya mereka ragukan bukanlah hal baru dalam pemilu. Banyak orang mengira hal ini terjadi karena kurangnya pendidikan politik atau rendahnya literasi informasi. Namun, penelitian dalam bidang psikologi politik menunjukkan bahwa keputusan memilih tidak hanya ditentukan oleh akal sehat atau data, melainkan juga oleh identitas sosial dan relasi kekuasaan di lingkungan terdekat (Aspinall & Berenschot, 2019).
Dalam konteks banyak komunitas di Indonesia, pilihan politik seseorang sering kali tidak berdiri sendiri. Pilihan itu terikat pada keluarga, tokoh lokal, jaringan pekerjaan, atau figur yang dianggap berjasa. Di beberapa desa, misalnya, tokoh masyarakat atau tokoh agama dapat memberikan arahan dukungan, dan anggota komunitas mengikuti bukan karena diperintah, tetapi karena loyalitas dan rasa menghormati hierarki sosial. Ini menunjukkan bahwa memilih adalah tindakan sosial, bukan hanya tindakan politik.
Pemilih mungkin mengetahui rekam jejak kandidat yang bermasalah, korupsi, kinerja buruk, atau ketidakpekaan sosial. Namun, memilih berbeda dapat menimbulkan risiko, dikucilkan keluarga, hubungan kerja terganggu, atau dianggap tidak kooperatif dalam lingkungan sosial. Dalam situasi seperti ini, stabilitas hubungan sosial dianggap lebih penting daripada integritas politik. Teori psikologi sosial menyebutnya normative social influence, kecenderungan mengikuti pilihan kelompok demi diterima dan menghindari konflik (Cialdini, 2003).
Di sisi lain, ada pula faktor ketergantungan ekonomi. Di beberapa wilayah, akses bantuan, pekerjaan proyek, atau kedekatan dengan pejabat lokal masih menjadi sumber keamanan ekonomi. Dari sini, pilihan politik menjadi bentuk transaksi perlindungan, sebuah cara untuk mempertahankan rasa aman di kehidupan sehari-hari. Maka, pemilu bagi sebagian masyarakat bukan hanya arena ide, tetapi arena bertahan hidup.
Situasi ini menciptakan paradoks, secara hukum suara adalah hak pribadi.
Namun dalam praktik sosial, suara sering menjadi tanggung jawab kelompok.
Di sinilah tantangan penyelenggaraan pemilu berada. KPU dapat terus meningkatkan kualitas sosialisasi, Bawaslu dapat memperketat pengawasan, dan DKPP dapat menjaga etika penyelenggara. Tetapi selama dimensi sosial dan budaya tidak disentuh, orientasi memilih tetap bertumpu pada loyalitas, bukan kemampuan kandidat.
Karena itu, pendidikan pemilih seharusnya tidak berhenti pada informasi tentang cara mencoblos atau konsekuensi politik uang. Ia perlu menyentuh kemampuan warga untuk berpikir mandiri dalam ruang yang aman. Bukan mengajak mereka melawan komunitasnya, tetapi memberi ruang refleksi bahwa peduli pada hubungan sosial tidak harus berarti menyerahkan suara hati sepenuhnya.
Pemilu yang baik bukan hanya yang berjalan tertib, tetapi yang memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk menggunakan suaranya sebagai ekspresi kesadaran, bukan sekadar penyesuaian terhadap tekanan lingkungan.
