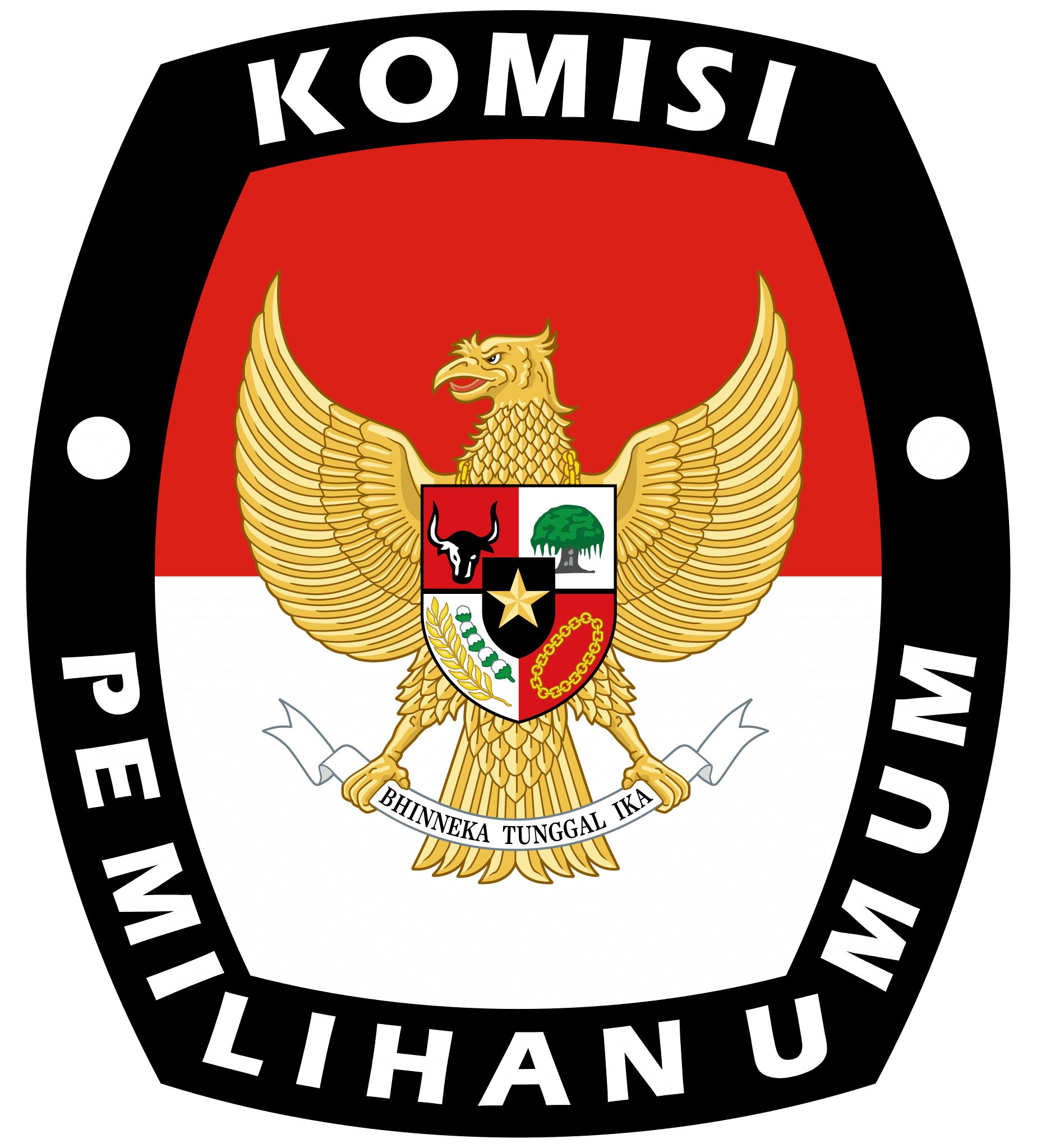Penyelenggaraan Pemilu di Negara Multikultural
Oleh : Lidia Wenny Penyelenggaraan pemilu di negara multikultural selalu menghadirkan tantangan tersendiri. Keberagaman etnis, bahasa, agama, dan identitas politik membuat proses elektoral bukan sekadar perhitungan suara, tetapi juga proses membangun rasa kebersamaan di tengah perbedaan. Peneliti pemilihan umum menegaskan bahwa legitimasi demokratis jauh lebih kuat ketika seluruh kelompok merasa terwakili dan memiliki akses setara untuk berpartisipasi (Lijphart, 1977). Karena itu, negara multikultural biasanya menekankan inklusivitas, aksesibilitas, dan mekanisme yang mampu menjembatani keragaman tersebut. Dalam banyak kasus, negara harus memastikan bahwa proses pemilu menjangkau seluruh wilayah dan komunitas, termasuk mereka yang tinggal di area terpencil atau memiliki karakteristik sosial yang berbeda. India sering dijadikan contoh klasik. Meskipun sudah menggunakan Electronic Voting Machine (EVM), penyelenggara pemilu India tetap menghadapi tantangan besar berupa distribusi perangkat pemungutan suara ke wilayah-wilayah yang sulit diakses, dari desa di pegunungan, komunitas kecil di pedalaman, hingga pulau terpencil. Tantangan ini menunjukkan bahwa teknologi memang membantu efisiensi, tetapi akses fisik untuk memastikan setiap warga dapat memberikan suara tetap menjadi pekerjaan besar di negara dengan keragaman geografis sekaligus multikulturalisme yang kuat. Selain itu, pemilu di negara multikultural menuntut pengelolaan narasi publik agar tidak terjebak pada politik identitas yang sempit. Horowitz (1985) menekankan bahwa kompetisi elektoral dalam masyarakat majemuk rentan memicu polarisasi jika tidak diimbangi dengan mekanisme representasi yang adil. Karena itu, beberapa negara menerapkan kebijakan afirmatif, pembagian daerah pemilihan khusus, atau model representasi proporsional untuk memastikan kelompok minoritas tetap memiliki ruang politik. Dalam konteks ini, penyelenggara pemilu bukan hanya administrator prosedural, tetapi juga aktor penting dalam menjaga stabilitas sosial. Akhirnya, kekuatan penyelenggaraan pemilu di negara multikultural terletak pada kemampuan sistem untuk mengakui keragaman tanpa membelah masyarakat. Pemilu yang inklusif, dapat diakses, dan dirancang untuk merangkul keberagaman menjadi fondasi penting bagi konsolidasi demokrasi. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa ketika semua kelompok merasa dihitung dan dihargai, hasil pemilu tidak hanya mencerminkan preferensi politik, tetapi juga memperkuat kepercayaan sosial yang menjadi inti dari demokrasi itu sendiri.
Selengkapnya