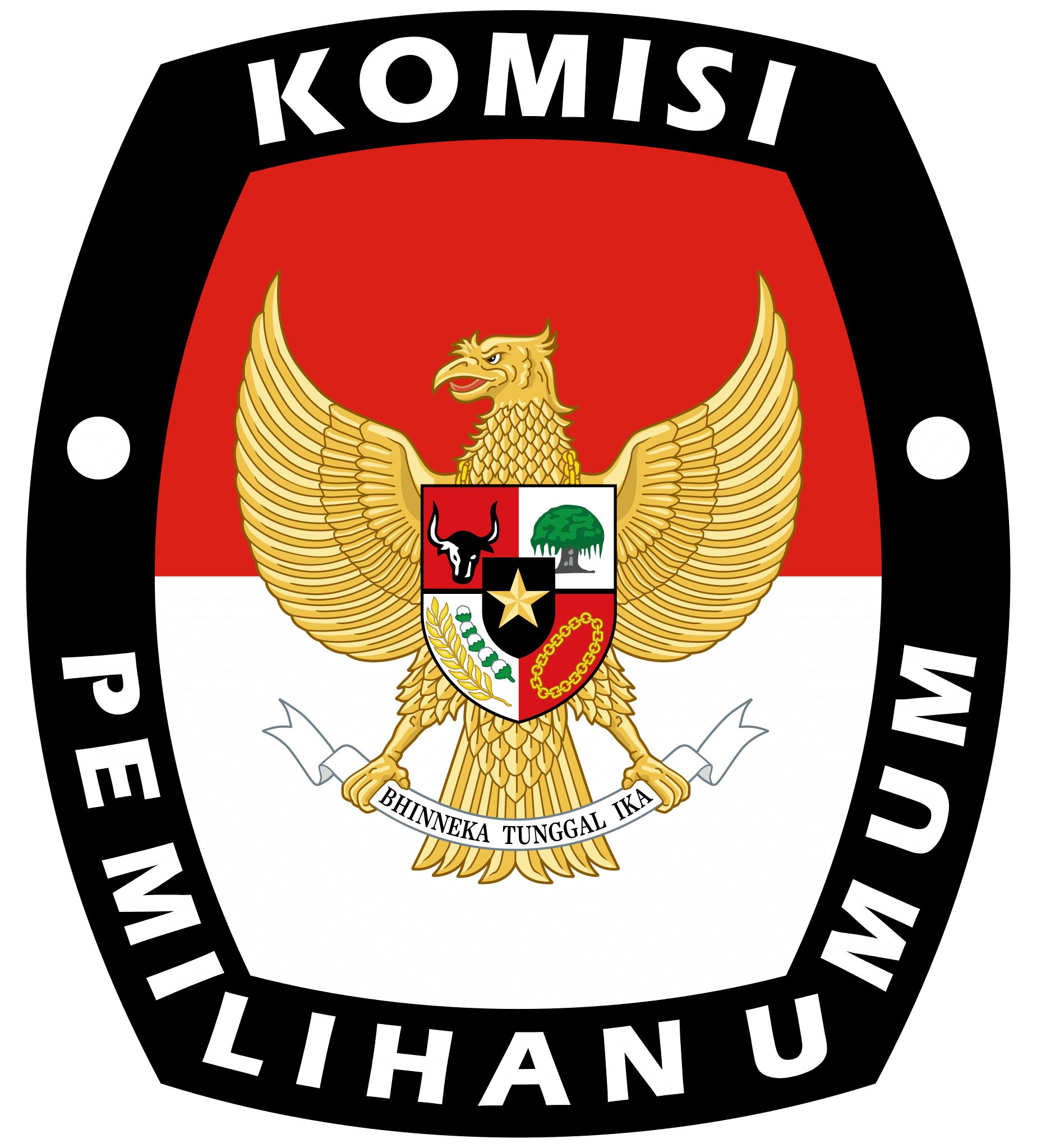Pemilu Inklusif : Apakah Sistem Kita Ramah bagi Difabel dan Marginal?
Penulis : Radha Florida
Pemilu inklusif merupakan fondasi utama bagi demokrasi yang adil dan merata, namun kenyataannya belum sepenuhnya terwujud dalam praktik di Indonesia, terutama bagi difabel dan kelompok marginal. Meskipun KPU telah melakukan berbagai upaya seperti mengusahakan pemilih difabel ditempatkan di TPS yang aksesibel dan membatasi jumlah pemilih per TPS agar bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal, masih ada kendala signifikan seperti masih luputnya pendaftaran pemilih disabilitas akibat ketidaktahuan keluarga.
Hal ini menunjukkan bahwa sistem kita memang mulai bergerak menuju inklusivitas, tetapi langkah tersebut belum cukup untuk menghapuskan hambatan struktural yang dihadapi difabel dalam menggunakan hak pilihnya. Bahkan dalam forum nasional Temu Inklusi 2025, para pemangku kebijakan menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur aksesibilitas yang memadai dan pengintegrasian perspektif disabilitas dalam kebijakan pemilu. https://inklusi.or.id/id/berita-cerita/berita/temu-inklusi-2025-difabel/
Secara regulatif, Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap inklusivitas. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan hak setiap warga untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah menunjukkan langkah konkret. Data KPU RI mencatat bahwa pada Pemilu 2024 terdapat 1,1 juta pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar mulai dari disabilitas fisik, sensorik, intelektual, hingga mental. Beberapa daerah bahkan melakukan inovasi seperti KPU Kabupaten Demak misalnya, menyiapkan TPS yang ramah kursi roda dan menyediakan pendamping bagi 4.354 pemilih difabel.
Langkah-langkah ini tentu menjadi kemajuan penting. Ia menegaskan bahwa negara mulai hadir untuk menjamin hak politik kelompok rentan. Namun, jika kita menelusuri lebih dalam, kenyataan di lapangan masih jauh dari kata ideal.
Laporan Perdik (Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan) menemukan bahwa 45 persen TPS yang dipantau tidak memiliki data pemilih difabel. Akibatnya, layanan aksesibilitas seperti jalur landai, panduan visual, maupun pendampingan bagi pemilih tunanetra dan tunarungu sering kali tidak tersedia. Bahkan, survei Kompas mencatat bahwa 54 persen difabel tuna daksa mengalami kesulitan saat mencoblos karena keterbatasan akses fisik di TPS. Lebih lanjut, 84 persen TPS tidak menyediakan juru bahasa isyarat, dan 69 persen tidak memberikan informasi tata cara memilih dalam bahasa isyarat.
Sementara bagi marginal seperti mereka yang tinggal di daerah terpencil, bekerja di sektor informal, atau tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap hambatan lain muncul. Banyak dari mereka tidak tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) karena mobilitas tinggi atau ketidaklengkapan administrasi. Akibatnya, hak pilih yang seharusnya dijamin konstitusi justru tidak dapat digunakan.
Namun, harapan tidak hilang. KPU, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas difabel kini semakin aktif bekerja sama untuk mendorong perubahan. Sosialisasi berbasis komunitas, pelatihan petugas tentang pelayanan inklusif, serta keterlibatan relawan muda dalam edukasi politik menunjukkan arah positif.
Narasi ini menunjukkan bahwa inklusivitas dalam pemilu bukan sekadar jargon. Ia harus diwujudkan dalam bentuk nyata seperti akses fisik yang memadai, informasi yang bisa diakses semua kalangan, pendidikan pemilih yang kontekstual, dan representasi politik yang mencerminkan keberagaman masyarakat. Tanpa itu, demokrasi kita belum sepenuhnya utuh. Demokrasi yang matang bukan diukur dari jumlah pemilih, melainkan dari seberapa jauh setiap individu termasuk difabel dan marginal merasa dihargai, didengar, dan dilibatkan.
![]()
![]()
![]()