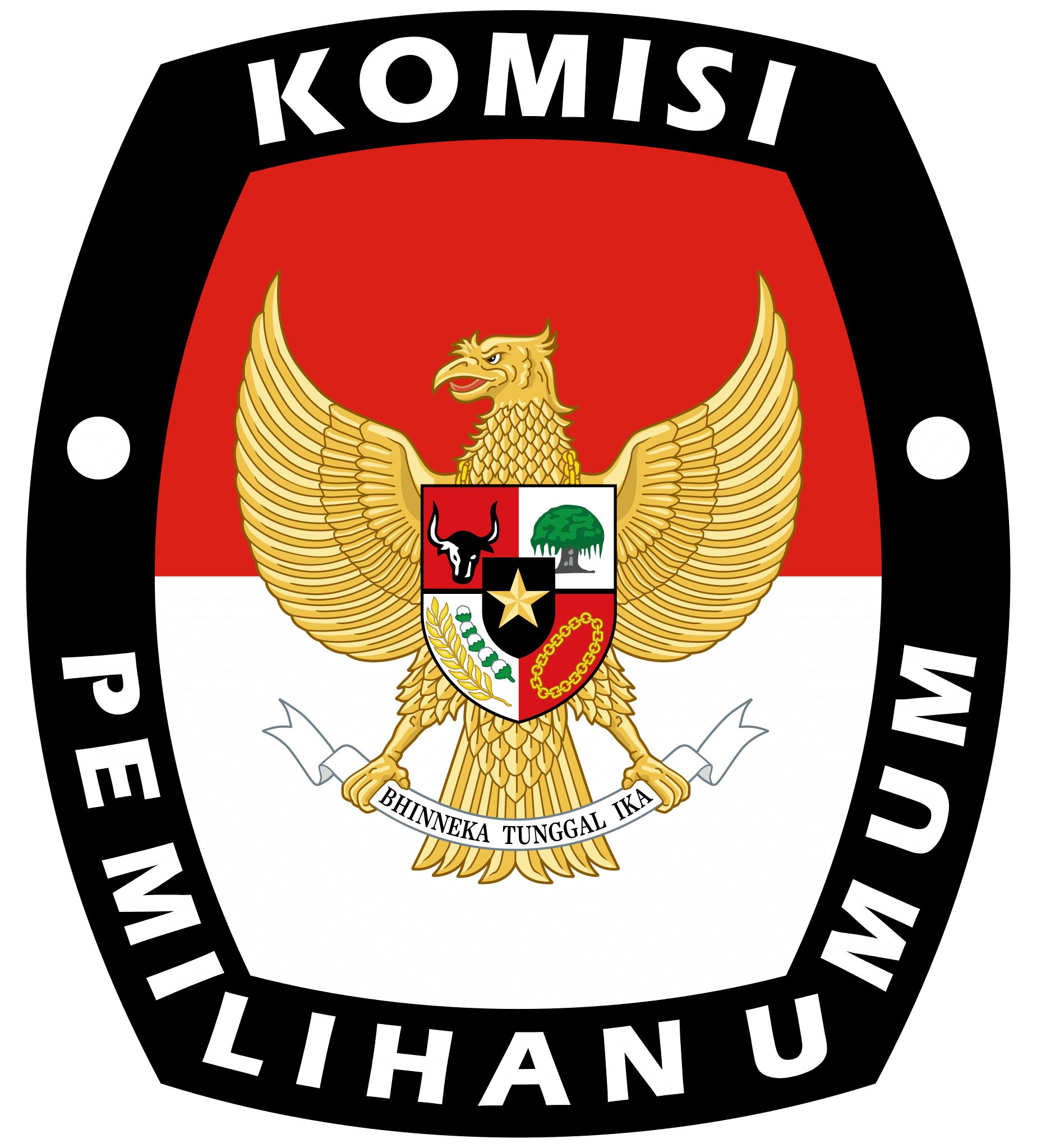VOTER TURNOUT DAN KUALITAS PEMILU
Saya tidak begitu kaget ketika membaca berita kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK), biasa saja…. Saya hanya tersenyum ketika membaca inisial mantan Gubernur tersebut menggunakan akronim AGK, karena akronim tersebut mengingatkan pada sosok guru saya yang biasa kami muridnya menyematkan panggilan Mas “AGK” alias Abdul Gaffar Karim.
Sampai saat ini masih terngiang di kepala saya ketika guru saya itu mengatakan “kenapa kita selalu mengkhawatirkan voter turnout (tingkat partisipasi pemilih), padahal seharusnya yang lebih khawatir terkait hal tersebut adalah partai politik”. Tanpa perlu merenung begitu panjang, saya mengamini pendapat tersebut, toh saya pikir kewajiban negara adalah menjamin hak sipil dan politik warga negaranya, alias menjamin setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat memilih untuk tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tentunya memiliki kebebasan dalam memilih.
Jika sekedar tingkat partisipasi pemilih yang harus digenjot, maka rezim Orde Baru punya resepnya. Pemilu tahun 1992 adalah buktinya. Pada waktu itu lebih dari 124 juta pemilih terdaftar dan tingkat partisipasi pemilih sebesar 112 juta atau sekitar 90,32%. Menteri dalam negeri kala itu, Yogie Suardi Memet mengklaim bahwa pemilu di Indonesia merupakan pemilu dengan partisipasi pemilih tertinggi di dunia (Schiller, 1999:1). Dalam pada itu, kita tahu bahwa pemilu era orde baru sudah dimanipulasi pemerintah dan hanya menjadi ritual yang disebut sebagai “pesta demokrasi” (Schiller, 1999:3).
Apa yang terjadi di Indonesia pada masa lalu tidak jauh dengan apa yang terjadi di Korea Utara. dalam pemilu legislatif di Korea Utara, partisipasi pemilih nyaris mencapai 100%. Dalam pemilu tersebut, pemilih menerima surat suara dengan hanya satu nama yang terdapat di dalamnya. Tak ada yang harus diisi, tak ada kolom yang perlu dicontreng, pemilih hanya perlu membawa surat suara dan memasukkannya ke dalam kotak suara yang diletakkan di tempat terbuka (https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47519704).
Memang tingginya partisipasi pemilih tidak melulu lekat dengan rezim otoritarian. Di Swedia misalkan, pada pemilu tahun 2022 jumlah partisipasi pemilih mencapai 84,21 persen dari pemilih yang memenuhi syarat. Swedia memang punya trend yang bagus dalam hal tingginya partisipasi pemilih yang tidak pernah kurang dari 80 persen sejak tahun 1950an. Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya jumlah pemilih di Swedia, yakni kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi, dan penghormatan terhadap sistem pemilu. (https://sweden.se/life/democracy/elections-in-sweden).
Mas AGK menggunakan istilah token of membership untuk menggambarkan “pemilu” yang hanya dijadikan bukti bahwa sebuah negara negara menganut demokrasi (dalam Pamungkas, 1999:viii-ix). Walaupun melaksanakan pemilu, semua orang juga sudah mengetahui bahwa bagaimana otoriternya Indonesa di era orde baru dan Korea Utara kini. Jadi tidak serta merta yang melaksanakan pemilu otomatis menjadi demokrasi.
Dalam konteks kekinian, saya kok lebih khawatir melihat maraknya praktik politik uang yang begitu massif ketika pemilu. Hasil riset charta politika (dalam Amal, 2022:594) yang menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia menganggap biasa terhadap adanya praktik politik uang di dalam pemilu kiranya menjadi pertanda buruk bagi kualitas pemilu kita.
Jadi gimana, masih khawatir tingkat partisipasi pemilih atau kualitas pemilunya?
Oleh: Hendrasyah Putra
![]()
![]()
![]()